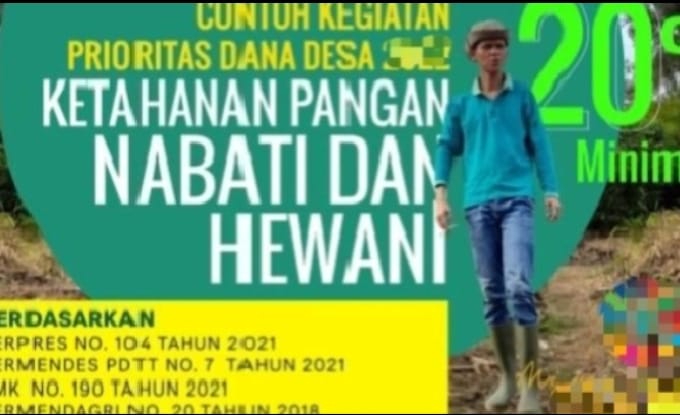Oleh : AHMADI SOFYAN
KALAU masyarakat Jawa menanam padi, pasti jalannya mundur, tapi kalau di Bangka menanam padi pasti jalannya maju
=====
DULU dimasa kecil, saya seringkali menyaksikan orang-orang “behume” atau “behuma” alias berladang, yakni menanam padi di ladang atau lahan kering. Biasanya ketika lahan ditebas dan dibakar, sebelum ditanami lada (setelah lada ditanami karet), maka yang pertama kali ditanam adalah padi. Sekitae 4-5 butiran padi dimasukin ke dalam lobang yang tidak begitu dalam yang dibuat dengan kayu (galah).
Tehniknya, kaum laki-laki dengan 2 buah galah panjang di kedua tangannya berjalan didepan sambil membuat lobang kecil seukuran galah yang dipegang. Galah-galah itu diangkat dan ditumbuk ke tanah. Lantas kaum perempuan dengan membawa 1 buah tempat butiran padi (seperti piring atau mangkok kecil) dan berjalan kedepan dengan cara berjongkok sambil meletakkan beberapa butiran padi ke dalam lobang. Nah, kalau masyarakat Jawa menanam padi, pasti jalannya mundur, tapi kalau di Bangka menanam padi pasti jalannya maju.
Laki-laki yang membawa 2 buah galah di kedua tangannya sambil berjalan membuat lobang dengan galah tersebut dinamakan Nugal. Umumnya masyarakat di kampung-kampung seringkali menyebut awal menanam padi ini dengan sebutan “nugal”. Sedangkan “behume” atau berladang kala padi sudah mulai tumbuh hingga panen. Umumnya nugal atau menanam butiran padi ini dilakukan dengan rame-rame atau gotong royong. Tuan rumah atau pemilik ladang menyiapkan makanan dan minuman. Selain nasi beserta lauk pauk sekedarnya, umumnya ada bubur kacang hijau. Kalau kopi dan teh itu sudah pasti disiapkan. Gelak tawa dan canda ria penuh keakraban biasanya menjadi ciri khas dalam kegiatan Nugal ini. Terlebih makannya ditengah hamparan ladang, semakin nikmat saja. Terakhir kali saya ikut kegiatan Nugal ini tahun 2019 di lahan sahabat masa kecil di Desa Kemuja.
Hasil dari panen padi inilah yang akhirnya disimpan (masih berbentuk padi) oleh para orangtua kita. Lantas diambil sesuai kebutuhan dan ditumbuk agar menjadi beras. Seiring perjalanan waktu, ada mesin pengelupas kulit padi. Padi-padi yang tersimpan inilah sebagai ketahanan pangan orangtua kita dulu, sehingga mereka sangat jarang membeli beras, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak membeli beras sebab banyaknya simpanan padi. 1 atau setengah karung butiran padi biasanya disimpan khusus dijadikan benih untuk nugal pada tahun berikutnya.
Orangtua kita dulu di Pulau Bangka tergolong cerdas dan solutif. Mereka menyadari bahwa kita hidup di Pulau kecil, yang sangat mungkin sewaktu-waktu stok beras dari luar Pulau bisa “mandek” akibat berbagai macam faktor. Sedangkan lahan yang ada umumnya adalah lahan kering bukan lahan persawahan seperti di Pulau Jawa. Jika pun ada lahan yang bisa dijadikan persawahan, selain lokasinya jauh, juga tempatnya tidaklah banyak.
Dari kesadaran inilah, para orangtua kita yang tak berpendidikan tinggi itu terdidik untuk menemukan solusi bagaimana kebutuhan utama berupa beras bisa terpenuhi bahkan tersimpan bertahun-tahun dalam lumbungnya.
Seiring perkembangan zaman dan perjalanan waktu, disertai modernisasi dalam berbagai sisi, berladang atau “behume” sudah jarang sekali kita saksikan. Kita masyarakat kampung akhirnya menjadi konsumen produk-produk dari luar ketimbang produksi dari lahan sendiri. Awalnya kita anggap lebih baik membeli, sebab harganya murah, daripada produksi (nanam) biayanya besar. Namun lama kelamaan kebiasaan menanam kita hilang oleh gaya kita sebagai penikmat. Terus harga-harga kebutuhan pokok yang awalnya kita anggap murah, ternyata sedikit demi sedikit naik dan melambung tinggi. Hendak kembali menanam, kebiasaan itu sudsh hilang dan generasi telah berganti tanpa tahu bagaimana berladang atau “behume”. Begitulah siklus elite global dalam “membantai” ekonomi kita di sisi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kecerdasan orangtua kita tidak sampai disini, tapi di lahan tersebut mereka bertanam berbagai jenis kebutuhan hidup sehari hari, dari kunyit, lengkuas, cabe, cekur, sayuran, tomat, kacang panjang, timun, kacang butur, dan lain sebagainya. Konon, saat itu hanya bawang, gula, garam, terasi dan sasa saja orangtua kita membeli di toko. Lebih cerdas lagi, ubi atau singkong ditanam diawal membuka lahan dan umumnya ditanam dipinggir lahan sebagai pembatas. Orangtua kita dulu berpendapat: “semiskin-miskinnya kita, insya Allah masih ada ubi/singkong untuk dimakan”. Bagi saya ini nilai kearifan lokal yang mengandung kecerdasan tinggi ditengah minimnya fasilitas modern seperti kita sekarang ini. Salut banget dengan pemikiran dan aksi orangtua kita zaman dulu.
Pertanyaan berikutnya adalah: Bagaimana solusi kita menyikapi harga beras yang kian naik dan rasanya tak mungkin turun? Apakah pemerintah kembali bikin pernyataan agar masyarakat mengurangi konsumsi beras atau cukup beli beras ukuran sachet di warung? Apakah mungkin kita kembali menggerakkan “behume” atau “beladang” dengan memanfaatkan banyaknya lahan kosong yang tak produktif di Bangka Belitung ini? Mungkinkah kita “behume” atau berladang diantara tanaman sawit yang masih kecil atau dibekas lahan tambang yang diolah? Atau mungkinkah para Kepala Daerah memanggil para pengusaha pemilik banyak lahan untuk dapat ditanami padi (beladang) bagi masyarakat dengan aturan yang dibuat sedemikian rupa lantas saling menguntungkan? Mungkinkah diantara tanaman-tanaman lain kita tanam butiran padi itu? Bukankah jerami padi memiliki manfaat besar bagi hewan dan tumbuhan lainnya?
Entahlah, harusnya Dinas terkait bersama para Kepala Daerah duduk bareng menemukan solusi untuk masyarakat. Insya Allah tak ada masalah yang berat, tapi akan terasa sangat berat kalau kita tidak memulai melakukannya.
Salam Behume!!
(Kebun tepi sungai, 25/02/2024)
====
Ahmadi Sofyan, akrab disapa Atok Kulop. Banyak menghabiskan waktunya di Kebun tepi sungai di Desa Kemuja. Selain 80-an buku karyanya sudah diterbitkan, 1.000-an opininya dimuat diberbagai media cetak & online.