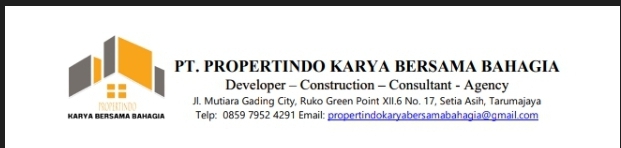Oleh: Adinda Putri Nabiilah SH
Bangka Belitung, Advokatnews.com — KASUS dr. Ratna membuka mata kita bahwa perlindungan tenaga kesehatan bukan hanya isu sektoral, tetapi problem tata kelola pemerintahan daerah. Babel sebagai provinsi kepulauan dengan keterbatasan dokter spesialis seharusnya menempatkan aspek perlindungan hukum tenaga kesehatan sebagai program strategis.
Saat seorang dokter spesialis yang memiliki kompetensi terbatas jumlahnya terjerat proses pidana tanpa penyaringan etik dan disiplin terlebih dahulu, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dokter tersebut, tetapi oleh seluruh masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan.
1. Babel Memerlukan Blue Print Perlindungan Tenaga Kesehatan
Pemerintah provinsi perlu menyusun:
Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang mengatur tata laksana pendampingan hukum, mitigasi sengketa, dan standardisasi komunikasi kasus medis.
* Pembentukan Medical-Legal Response Team di tiap rumah sakit daerah.
* Program capacity building tentang etika komunikasi medis, mediasi konflik, dan keselamatan pasien.
Tidak bisa lagi tenaga medis dibiarkan menghadapi persoalan hukum seorang diri.
2. Peran Pemerintah Daerah: Dari Diam Menjadi Aktif
UU Rumah Sakit (UU 44/2009) dan PP No. 47/2016 menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas:
* mutu pelayanan,
* keselamatan tenaga kesehatan,
* standar operasional layanan,
* dan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan.
Dalam konteks ini, Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang seharusnya:
* turun langsung memonitor penanganan kasus,
* memastikan pendampingan hukum profesional,
* serta mengawasi apakah RSUD Depati Hamzah telah menjalankan kewajiban governance-nya.
Di banyak daerah, kepala daerah sering tampil sebagai inisiator pembenahan sistem kesehatan. Babel tidak boleh berada di posisi reaktif.
3. Perlu Keberanian IDI & IDAI Babel untuk Berubah Menjadi Organisasi Advokatif
Organisasi profesi bukan sekadar tempat berkumpulnya para dokter, melainkan pilar hukum bagi perlindungan profesi.
IDI dan IDAI harus:
* memiliki legal task force yang selalu siap menangani kasus serupa,
* melakukan pendampingan sejak fase awal masalah, bukan setelah kasus membesar,
* aktif mengedukasi publik dan aparat penegak hukum tentang batasan-batasan medis.
Jika organisasi profesi pasif, maka dokter semakin rentan menghadapi kriminalisasi.
4. Penegak Hukum Perlu Membangun Sensitivitas terhadap Kasus Medis
Pasal 50 dan Pasal 51 UU 29/2004 jelas menyatakan bahwa dokter memiliki perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai standar. Oleh karena itu, penyidik seharusnya:
* meminta pendapat ahli,
* memeriksa standar pelayanan,
* melakukan klarifikasi terhadap mekanisme etik dan disiplin,
* dan menahan diri untuk tidak buru-buru menetapkan tersangka sebelum menemukan bukti malpractice yang nyata.
WHO dan berbagai literatur hukum kesehatan menegaskan bahwa penanganan kasus medis membutuhkan clinical approach bukan criminal approach.
5. Membangun Budaya Just Culture untuk Mengurangi Ketakutan
Just Culture membedakan:
* human error (kesalahan manusia yang wajar),
* at-risk behavior (perilaku berisiko karena sistem tidak memadai),
* reckless behavior (kelalaian serius yang patut dihukum).
Jika semua insiden medis dianggap pelanggaran pidana, maka tenaga kesehatan akan bekerja dengan rasa takut. Ini berbahaya bagi masyarakat karena memicu:
* banyaknya rujukan tidak perlu,
* lambatnya pengambilan keputusan gawat darurat,
* meningkatnya biaya kesehatan,
* dan menurunnya akses pelayanan terutama di daerah pelosok.
Babel yang kekurangan dokter tidak boleh membiarkan budaya takut tumbuh dalam sistem kesehatan.
Penutup: Saatnya Babel Mengambil Langkah Besar
Kasus dr. Ratna Setia Asih hanyalah puncak gunung es dari persoalan tata kelola kesehatan yang lebih besar. Tidak ada yang diuntungkan ketika tenaga kesehatan bekerja dalam ancaman kriminalisasi. Masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak ketika dokter mulai enggan mengambil keputusan klinis yang berisiko, meskipun demi menyelamatkan nyawa.
Karena itu:
* rumah sakit harus memperkuat governance,
* organisasi profesi harus tampil sebagai pembela anggotanya,
* pemerintah daerah harus mengambil peran strategis,
* aparat penegak hukum harus lebih memahami karakteristik sengketa medis,
* dan publik perlu mendapatkan edukasi yang tepat tentang risiko medis.
Kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi Babel. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh sehingga dokter dapat bekerja aman, masyarakat terlindungi, dan layanan kesehatan dapat terus berkembang.
Jika Babel mampu menjadikan kasus ini sebagai momentum reformasi, maka dari sebuah tragedi dapat lahir sistem kesehatan yang lebih kuat, manusiawi, dan berkeadilan.
————————————————————Penulis : Adinda Putri Nabiilah, S.H.,C.IJ., C.PW. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI) Tahun 2023 saat ini menjadi Editor di Jejaring Media KBO Babel.
Saran & Masukan terkait dengan tulisan opini silahkan disampaikan ke nomor redaksi 0812-7814-265 atau 0821-1227-4004