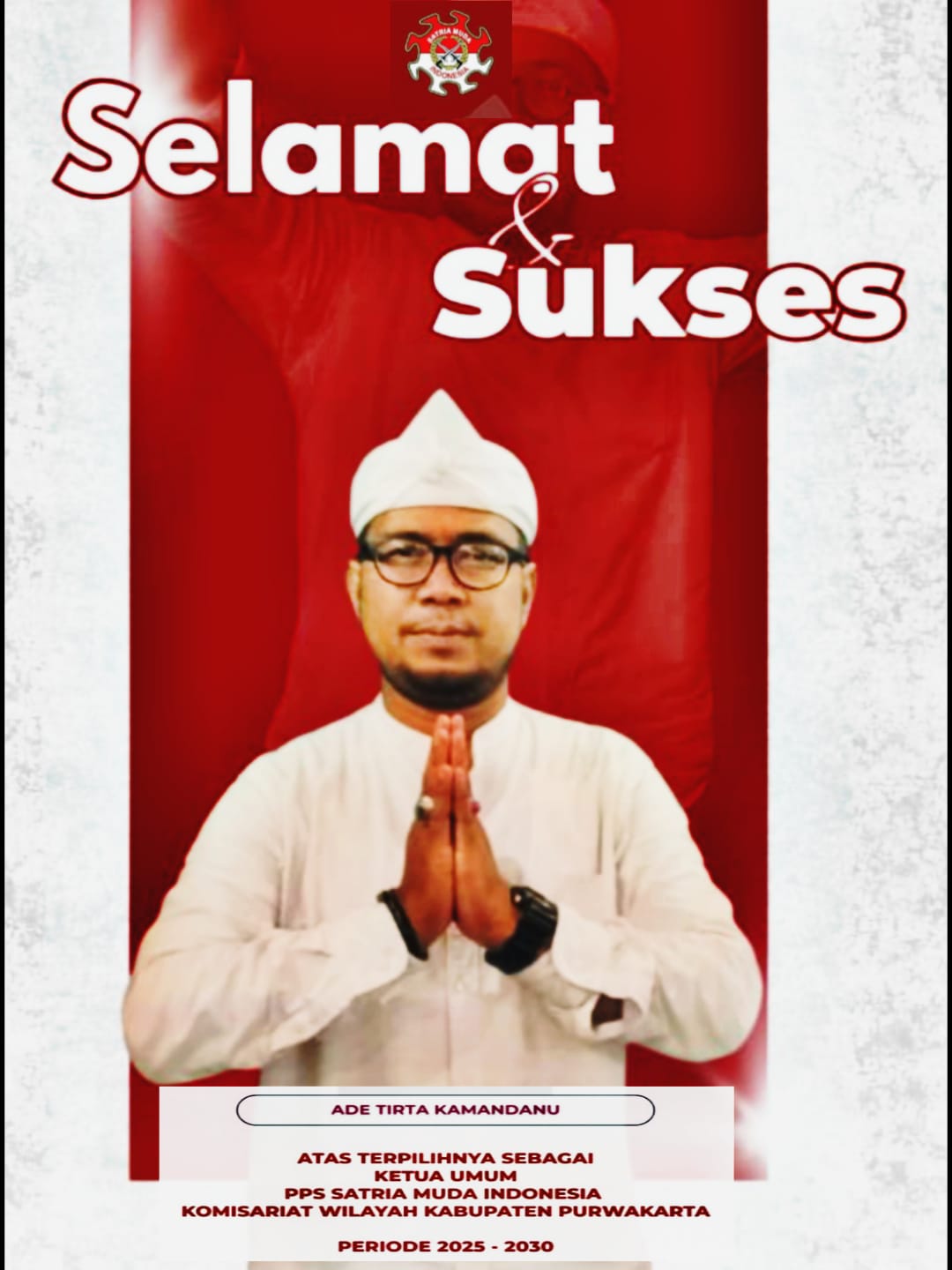Oleh : AHMADI SOFYAN
IBARAT Rak di dapur, didalamnya piring, gelas, teko, sendok, garpu, mangkok, pisau, toples, dan lain sebagainya sesekali bunyi “kelontang-kelonteng” akibat berbenturan. Begitulah demokrasi….
====
DEMOKRASI bukanlah baliho atau sepanduk, tapi salah satu tanda berjalannya demokrasi di negara kita adalah dengan menampilkan baliho dan spanduk sebagai pengenalan bagi masyarakat. Bagi saya pribadi, baliho atau spanduk sepanjang jalan di musim Pemilu seperti sekarang ini bagian dari keasyikan sendiri. Bendera partai berjejer, selama tidak mengganggu jalan dan baliho atau spanduk selama tidak dipaku di pohon hidup, oke-oke saja.
Di musim Pemilu seperti sekarang ini, banyak yang protes, mencemooh, menghujat, mencaci, mengolok dan sebagainya baliho & spanduk Caleg. Padahal kan cuma 5 tahun sekali, itung-itung rezeki tukang cari kayu, tukang pasang baliho dan tukang cetak baliho dan sepanduk. Warna-warni bendera, spanduk dan baliho adalah wajah demokrasi kita yang masih menghargai berbagai perbedaan dan pertanda kekayaan negeri. Kita kaya akan kader-kader yang siap mengabdi pada negeri melalui legeslatif.
Perbedaan itu rahmat yang sangat luar biasa. Bayangin kalau orangtua kita tidak berbeda alias sejenis, pasti kita tak pernah ada di muka bumi ini. Makanya nikah itu gak apa-apa beda suku, budaya, beda kampung, beda wajah, beda status sosial, beda profesi, yang paling penting beda jenis kelamin. Setiap perbedaan itu ketika akur dan harmoni, pasti melahirkan sesuatu yang baru.
Perbedaan pilihan dalam demokrasi ada keasyikan tersendiri. Riuh dan debat alias “becelekeh” itu lumrah, yang penting tak saling membantai. Seringkali saya ungkapkan, politik itu cukup sampai tenggorokan jangan sampai masuk ke hati, ntar sakit hati. Kalau cuma sampai tenggorokan paling sakit tenggorokan alias habis suara.
Orangtua kita dulu pernah menasehatkan: “Selama sendok, garpu, piring, cangkir, mangkok & perabotan lainnya masih dalam satu rak, maka dipastikan berbenturan dan berbunyi “klontang-klonteng”.
Nasehat orangtua kita ini bermaksud untuk kita bijak dalam menghadapi perbedaan, “klontang-klonteng” mah sudah biasa, yang penting jangan sampai pecah. Gambaran dalam kehidupan kita, terjadi gesekan dan kadangkala suara keras yang mengagetkan sekitar, baik itu dalam komunitas, organisasi, perkumpulan, organisasi, lembaga, instansi bahkan pasti juga dalam keluarga.
Budaya Sebagai Lem Perekat
BUDAYA adalah kekayaan yang tercipta dari nilai-nilai kearifan (local wisdom). Budaya adalah jalan besar nan indah menjadi lem perekat bangsa Indonesia. Ketika Bhennika Tunggal Ika dicetuskan sebagai semboyan kita, menunjukkan betapa budaya Indonesia yang teramat kaya dan indah ini menyatu dalam kebersamaan sebagai anak bangsa.
Pemahaman budaya yang rendah, rentan akan membuat bangsa ini berpecah belah. Apalagi generasi Gen Z dan Milenial yang semakin menjauh dari nilai-nilai budaya, sehingga adab dan etika serta penghormatan pada nilai-nilai sejarah dan budaya sangatlah minim. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah dari Pusat sampai Desa untuk kembali menggali nilai-nilai budaya sebagai karakter bangsa. Sebab tahun demi tahun, Indonesia berkarakter budaya semakin tak jelas. Budaya itu bukan setiap tahun pada peringatan 17 Agustus dengan memakai busana adat suatu daerah. Itu hanya penampakan saja, yang paling penting adalah kebijakan dan membentuk watak.
Sejarah dan budaya adalah lem perekat, jangan sampai para pengambil kebijakan, pengelola negeri bahkan cukuplah sudah para anggota legeslatif yang tidak paham budaya daerah dimana ia mewakili duduk sebagai Wakil kita. Pilihlah Capres yang akan mengokohkan budaya sebagai karakter bangsa. Pilihlah Caleg yang paham daerah yang ia wakili, bukan Caleg transferan “ujug-ujug’ datang dari daerah lain, lantas sok peduli dengan rumah tangga kita (daerah kita). Nah…., ini bagian dari cara ber-“klontang-klonteng” dalam demokrasi.
Itulah demokrasi, “klontang-klonteng” itu biasa.
Salam Klontang-Klonteng!!!
(Kebun Tepi Sungai, 30/01/2024)
====
AHMADI SOFYAN, dikenal panggilan Atok Kulop dan banyak menghabiskan waktu kesendiriannya di Kebun tepi sungai. Sudah menulis 80 an buku & 1.000 opini di media cetak & online. Berprofesi sebagai pengangguran namun mengaku sebagai tukang kebun (petani).