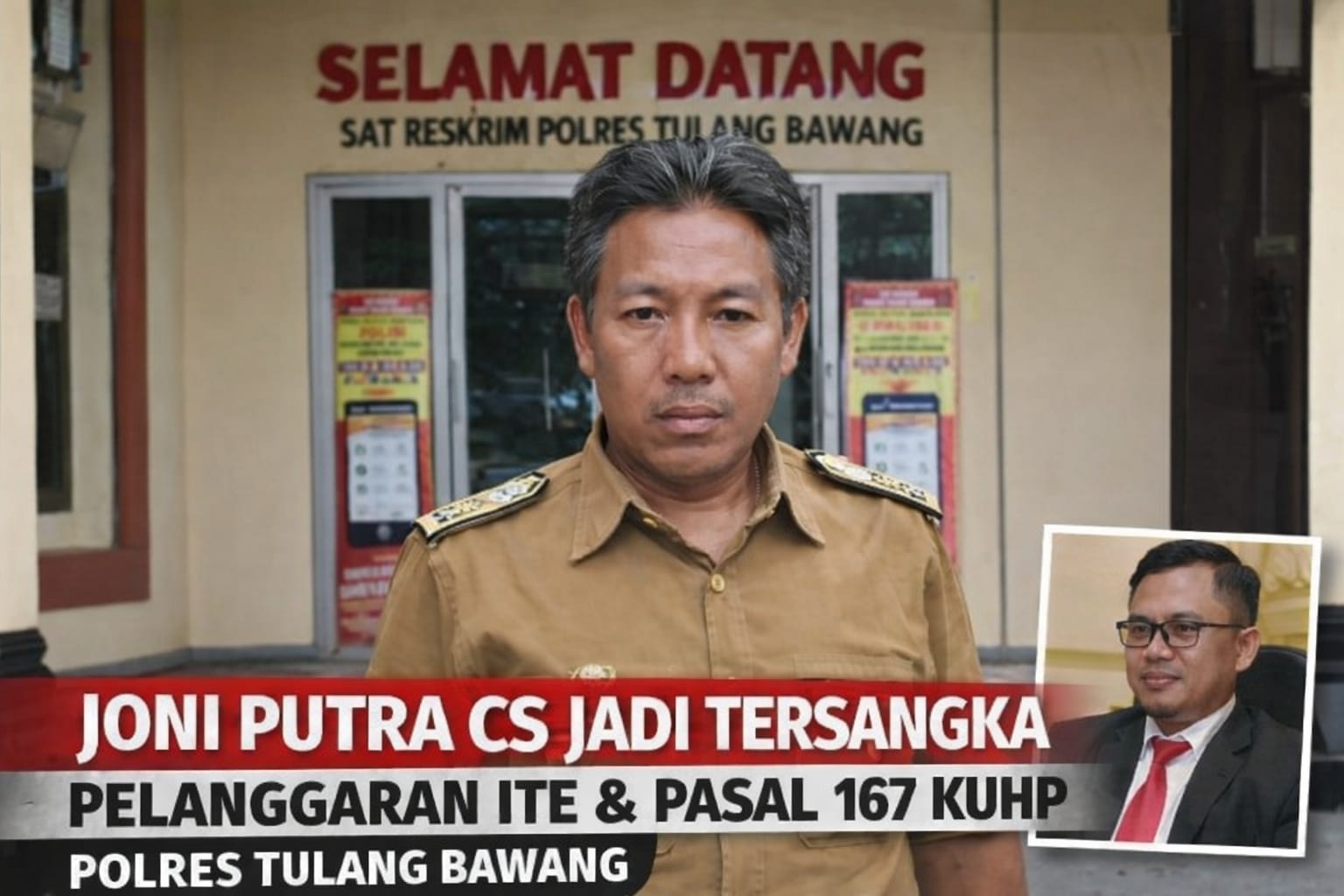Oleh: AHMADI SOFYAN
Setinggi apapun jabatan dan sepopuler apapun nama seorang murid, jangan pernah seorang guru membungkukkan diri & menghormati muridnya, sebab itulah awal kerusakan mental sang murid.
====
AMARRU Muftie Holish, anak muda asli Bangka yang baru saja menyelesaikan pendidikan S-2 nya di University of Basque Country Spanyol bertandang ke pondok kebun saya yang berada tepat di tepi sungai. Kami lama sudah berkomunikasi, saat ia masih di Spanyol. Ia mengenal nama saya dari ayahnya yang memang sahabat baik dan senior saya. Menurut Muftie Holish, Ayahnya jualah yang merekemondasikan nama saya untuk berkomunikasi dan diskusi dengan putra kesayangannya ini.
Sambil menikmati secangkir kopi dan memandang aliran sungai yang tak begitu deras, saya & Muftie Holish berdiskusi banyak hal, terutama tentang kehidupan sosial, tanah kelahiran Bangka Belitung, politik dan inspirasi sosial bagi anak-anak muda. Ternyata ada kesamaan saya dan Muftie Holish ini, sama sama pengagum Bj. Habibie. Kami berdua sama-sama menganggap & menyatakan bahwa Bj. Habibie adalah Negarawan sejati bagi Indonesia. Perjalanan politik dan kesahajaan serta buku-bukunya yang sama-sama pernah kita baca menjadi bahan diskusi yang menyenangkan sore itu. Saya suka diskusi dengan anak muda yang santun, tawadhu (mirip ayahnya) dan penuh rasa ingin belajar seperti Muftie Holish ini.
Berjam-jam kami berdua diskusi, tidak secuil pun Muftie Holish menceritakan apalagi membanggakan tentang perjalanan pendidikannya di luar negeri. Tidak ada sekalimat pun dirinya menceritakan dan membanggakan sang ayah yang notabene adalah orang yang sangat berpengaruh dan memiliki jabatan yang mentereng yang pastinya diimpikan oleh banyak orang.
Muftie Holish tidak menjadikan perjalanan pendidikannya di luar negeri sebagai ajang kehebatan untuk membanggakan diri. Ia juga tidak berada dibawah nama besar ayahnya yang juga sangat dekat dengan saya, bahkan kalau saya nggak ada duit, berani WhatsApp langsung dan minta sama ayahnya. Begitulah kedekatan saya sama Ayah dari anak muda usia 23 tahun ini. Muftie Holish menjadi dirinya sendiri, tanpa embel-embel kebesaran nama & jabatan sang Ayah atau perjalanan pendidkan yang ditempuh. Mungkin seperti ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib r.a. dalam wasiatnya: “Innal fata man yakuulu haa ana zha, walaiysal fathaa man yakuulu kaa na abii…” (Pemuda itu berani berkata inilah diri saya, bukan ini bapak saya)
Dalam diskusi tak bertepi itu, tiba-tiba saya memberikan nasehat kepada Muftie Holish yang berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Nggak tahu juga, nasehat ini belum pernah saya ucapkan sebelumnya kepada siapapun, sebab pengalaman ini sempat membuat saya sedikit khawatir dalam perkembangan mental saya kala itu.
Suatu hari, saya mendapat telpon. Melalui suara telpon itu, nada bicara yang sangat santun dan penuh penghormatan yang tinggi nampak terdengar oleh saya dari suara telpon yang saya genggam. “Assalamualaikum Pak Ahmadi”. Saya pun menjawab salam tersebut. Setelah sang pemilik suara menyebutkan namanya, saya kaget dan berusaha mengakrabkan diri dengan menanyakan kabar.
Setelah itu sang pemilik suara diujung telpon itu berkata dengan sangat santun dan seperti ragu-ragu menyampaikannya. “Jadi begini, kira-kira kapan Pak Ahmadi ada waktu, saya mau menghadap”. Mendengar omongan ini, tenggorokan saya seperti tercekat. Sesaat saya terdiam dan tak terasa kedua bola mata saya berkaca-kaca. Kalimat itu sangat biasa sekali sebab seringkali pertanyaan itu saya dapatkan. Tapi kali ini sangat berbeda dan tak akan pernah saya samakan sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Mengapa? Sebab yang mengucapkan itu adalah Guru saya selama 6 tahun saya dididik dan diajari oleh beliau semasa duduk di Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di Pondok Pesantren Al Islam Kemuja.
2 kalimat yang membuat saya sangat risih sekaligus khawatir, yakni kalimat panggilan “Pak” dan “menghadap” tepatnya“….kapan Pak Ahmadi ada waktu, saya mau menghadap?”. Sesaat terdiam, akhirnya saya menjawab pelan: “Pak, saya ini murid Bapak, sampai kapan pun saya adalah murid. Kenapa saya dipanggil “Pak Ahmadi?” Kenapa Bapak yang harus menghadap saya? Bukankah saya murid dan bapak adalah guru? Harusnya saya yang bapak panggil ke rumah dan saya yang harus datang serta menanyakan kapan bapak ada waktu saya datangi ke rumah?” begitulah jawaban yang saya berikan dengan sedikit terbata-bata sebab tenggorokan rasanya susah mengeluarkan suara.
“Bukan begitu, kamu kan sibuk?” bantah sang guru ini. “Nggak Pak. Kapan Bapak ada di rumah, saya mau datang” tegas saya dari ujung telpon. Akhirnya sesuai waktu yang ditentukan, saya datang menemui sang guru itu di kediamannya.
Kepada Muftie Holish saya katakan bahwa kesimpulan dari cerita pengalaman ini adalah etika sosial seorang murid kepada guru pasca sang murid sudah dewasa atau tak lagi dididik dan diajar. Apapun profesi yang kita sandang, setinggi apapun jabatan yang didapatkan dan sepopuler apapun nama kita dikenal orang, bahkan wira-wiri wajah kita nongol di televisi dan koran, kita tetaplah murid. Sebagaimana kita dihadapan orangtua kandung yang sesungguhnya hanyalah anak, bukan siapa-siapa dan tak terpedaya dengan apa yang sedang kita miliki.
Saya sangat suka kalau guru-guru yang pernah mendidik & mengajar saya datang ke kediaman saya, baik di kampung, di kebun maupun saat saya di rumah yang berada di Kota Pangkalpinang. Sebab itu sering terjadi dan hal seperti ini adalah keberkahan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang murid. Tapi mereka datang sekedar untuk berbincang ringan, ngopi, cerita ngalor ngidul atau sekedar menikmati masakan yang ada di rumah, bukan karena mereka membutuhkan saya. Kalau guru membutuhkan saya, maka saya yang harus dipanggil, bukan didatangi apalagi diminta waktu alias jadwal sempatnya. Memang sekurang ajar apa sang murid kok sampai guru yang harus menghadap? Terus terang, kurang ajar saya masih belum masuk tingkatan ini, walaupun tingkatan kurang ajar yang lain pernah saya jajaki.
Saya bangga banget, setelah dewasa ini, sering kumpul dan didatangi guru-guru, lantas dicandain atau dibully. Saya bahagia ketika guru-guru yang pernah mendidik & mengajar saya “ngerjain” atau mencandai dengan penuh keakraban yang mengundang tawa. Sebab kalau sudah seperti itu, saya menganggap mereka benar-benar akrab dan sudah menjadi sahabat dalam pergaulan, namun tetaplah Guru dan Murid yang tak akan boleh dikesampingkan.
Kepada Muftie Holish saya katakan bahwa mental kita sebagai manusia beretika & beradab mulia akan rusak jika sampai kita bangga dan menanggap diri hebat karena guru saja menghormati kita yang notabene pernah menjadi muridnya. Jangan pernah sepelekan persoalan seperti ini.“Suatu saat mungkin kamu akan mengalaminya, sebab saya yakin kamu sukses dan guru-gurumu bangga sama kamu. Tapi ingat, kamu harus tetap menjadi murid” Entah mengapa sore itu saya begitu sok banget memberikan nasehat etika kepada Muftie Holish yang notabene jauh lebih santun, tawadhu dan jelas beretika dibandingkan saya yang slenge’an ini.
Dari cerita ringan saya ini, sebetulnya pointnya sangat sederhana, yakni setinggi apapun jabatan dan sepopuler apapun nama seorang murid, jangan pernah seorang guru membungkukkan diri & menghormati muridnya, sebab itulah awal kerusakan mental sang murid.
Masihkah etika penting bagi manusia modern? Bagaimana etika pejabat negara bahkan Kepala Negara atau Wakilnya nanti? Ah, ketika konstitusi dikangkangi, demokrasi dicurangi, jangan bicara etika deh. Kalaulah tak pernah menjadi Guru, biasanya kalau diberi kesempatan memimpin dan berada didepan pasti menggurui, tapi…. pas ditanya jawabannya gak jelas dan plonga-plongo…! Itulah I N D O N E S I A……
Salam Etika!
(Kebun Tepi Sungai, 22/02/2024)
====
Ahmadi Sofyan, dikenal akrab dengan nama Atok Kulop. Pernah menjadi Guru di Pondok Modern Al-Barokah Kertosono Nganjuk. Selanjutnya ia terus menerus menjadi murid. Banyak menulis buku dan berbagai opininya dimuat diberbagai media cetak & online. Ia banyak menghabiskan waktunya di kebun tepi sungai.